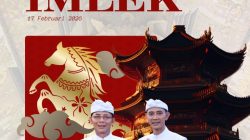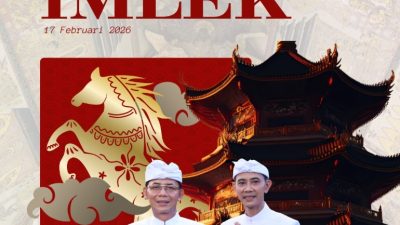Singaraja, Balijani.id ~ Dewasa ini, kehidupan manusia melekat dengan berbagai macam alat-alat teknologi canggih dan pola kebudayaan baru yang dapat ditemukan di belahan dunia lain. Ini menandakan bahwa kita memang sedang berada dalam pengaruh globalisasi yang jelas sudah mengaburkan batas-batas geografis, ideologis, dan kultural (borderless).
Praktik globalisasi kenyataannya tidak akan pernah terlepas dari fenomena globalisasi yang mempunyai tiga citra (image), yakni citra pembaratan-modernisasi, citra hegemoni dan dominasi, serta citra integrasi pasar global. Lantas, secara sadar atau tidak, perihal tersebut membentuk paradigma pemikiran baru yang mengarah pada sebuah istilah bernama neoliberalisme. Dalam dunia neoliberal, permasalahan bukan dinilai dari soal-soal etis mengenai sanksi dan rehabilitasi, melainkan selalu dilihat dari nilai ekonomi yang didapat oleh ‘seseorang’ (bernama A) dari konsekuensi aktivitas ‘seseorang yang lain’ (bernama B) agar mengeluarkan nilai ekonominya atas aksi yang dilakukan dan merugikan ‘seseorang’ (bernama A).
Kilas Balik Neoliberalisme terkait Pendidikan Tinggi di Indonesia
Sederhananya, neoliberalisme merupakan sistem ekonomi pasar bebas (free trade) yang berusaha memperluas kekuasaannya melalui privatisasi sektor publik, seperti misalnya pendidikan tinggi. Melalui formula dasar (deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi), neoliberalisme selalu percaya pada penghapusan peran negara di setiap aspek. Tidak heran bahwa para aktor yang mendukung paham ini terbilang bukan lembaga yang kecil, melainkan oleh otoritas kapital (yang memiliki power kuat), seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), Asian Development Bank (ADB) dan perusahaan multinasional (multinational corporation) lainnya. Uniknya, ‘mereka-mereka’ ini cukup semangat bilamana terdapat agenda atau wacana liberalisasi sektor, seperti pendidikan tinggi — dengan cara mengurangi intervensi pemerintah lokal terkait kebijakan pendidikan tinggi — melalui sebuah tema acara tentang otonomi pembiayaan bernama “reformasi pendidikan tinggi”.
Lebih jelasnya, para aktor tersebut memang pintar karena mampu melihat satu celah pada masa Orde Baru (era kepemimpinan Pak Harto) mengingat pemimpin saat itu terbilang ‘ramah’ dengan tamu-tamu asing, terutama Barat. Pada saat itu, tamu-tamu Barat tersebut mulai mengintervensi kebijakan Indonesia pasca-krisis melalui UU nomor 8 tahun 1966 tentang pendaftaran Indonesia sebagai anggota Asian Development Bank, UU nomor 9 tahun 1966 tentang pendaftaran kembali Indonesia sebagai anggota IMF dan World Bank, dan juga UU nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Beberapa undang-undang tersebut dijadikan dasar regulasi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, dengan adanya perjanjian GATS (General Agreement on Trade in Services), maka Indonesia turut serta dalam liberalisasi 12 sektor jasa, termasuk didalamnya sektor jasa pendidikan.
Dalam perjalanan praktiknya, Indonesia mulai mengikuti dan menerapkan langkah liberalisasi sektor jasa pendidikan di Amerika Serikat, yang kala itu melakukan privatisasi pendidikan tinggi (mengubah status universitas publik menjadi badan hukum). Pada tahun 1999, fenomena-fenomena liberalisasi, privatisasi, bahkan komersialisasi oleh segelintir pihak pun mulai terlihat — terbukti melalui Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pengelolaan perguruan tinggi, dan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang penetapan perguruan tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
Keputusan terkait langkah pemerintah Indonesia saat itu dilakukan dengan alasan bahwa terdapat peningkatan penyelesaian sekolah menengah dan tingginya permintaan akan lulusan yang terampil (Hill dan Wie 2013, 161). Tidak cukup sampai disitu, reformasi sektor pendidikan pun diwujudkan mengingat otonomi dan akuntabilitas kelembagaan menjadi isu strategis. Demi isu-isu strategis tersebut-lah UU nomor 22 tahun 1999 hadir melalui Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1999 guna memfasilitasi agenda perubahan universitas negeri menjadi universitas otonom yang berstatus badan hukum milik negara, sekaligus pula untuk menjaga prinsip desentralisasi pendidikan itu sendiri.
Teguran terhadap Neoliberalisme dalam Pendidikan Tinggi di Indonesia
“Apakah hingga saat ini kita sudah sepenuhnya sadar bahwa ada sesuatu yang aneh dalam pendidikan tinggi? Bagaimana maksudnya?”
Selama ini, alih-alih menjadi institusi yang netral, perguruan tinggi malah dijadikan sebagai ‘pabrik reproduksi’ faktor produksi sekaligus aset utama para korporat untuk dikomersialisasikan. Sadar atau tidak, penyematan status PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum) dalam UU nomor 12 tahun 2002 hanyalah dalih otonomi kampus belaka alias berbeda dengan penerapannya. Pada Pasal 88 UU no 12 tahun 2002 tentang UKT tersebut, biaya kuliah sebenarnya dinaikkan sebesar 100 hingga 300 persen dari dana awal. Bahkan, undang-undang tersebut nyatanya didukung oleh Permendiknas nomor 55 tahun 2013 yang mengatur penerimaan UKT golongan satu dan dua masing-masing 5%. Ini berarti pemerintah hanya membantu sebesar 10% rakyat yang membutuhkan bantuan pendidikan, sedangkan 90% lainnya harus memikirkan sendiri nasib pendidikannya — walaupun seringkali yang ‘terlihat’ adalah penggaung-gaungan atas banyaknya berita-berita beasiswa. Sangat miris mengingat bahwa jurang kesenjangan sosial di Indonesia masih cukup ‘lapang’ dan tidak ada penurunan secara signifikan.
Setelah membaca singkat tentang ‘kilas balik neoliberalisme’ sebelumnya, berulang kali kita patut sadari bahwa terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan akibat privatisasi yang tidak pernah lepas dari campur tangan ‘tamu-tamu’, seperti WTO tadi, yang cukup nafsu mengintervensi kebijakan dan sistem negara-negara berkembang, tanpa terkecuali Indonesia. Akibat dalih (yang juga sudah dijelaskan sebelumnya) ‘otonomi kampus’ ini, yang selanjutnya justru terjadi adalah keputusan dimana kampus akan mencari sumber pendanaan di luar negara, seperti misalnya perusahaan dan bank-bank swasta yang diajak bekerjasama, atau dari masyarakat itu sendiri melalui uang kuliah tunggal yang golongannya mengalami kenaikan.
Henry Giroux (1998) dalam The Business of Public Education memandang fenomena privatisasi universitas publik sebagai: a local industry that over time will become a global business. Fenomena privatisasi melalui berbagai bentuk ini akan mengubah tidak hanya institusi pendidikan yang menjadi institusi pasar demi mengejar profit, tetapi juga mengubah input, process, dan output pengelolaan universitas publik seluruhnya. Kemudian, imbasnya kembali lagi dibebankan kepada masyarakat sebab mereka akan dapat menyimpulkan bahwa membayar pajak yang tinggi demi memenuhi kepentingan pemerintah yang kabarnya mengalokasikan anggaran negara ke dalam penyelenggaraan pendidikan hanya sebatas kesia-siaan. Menurut Giroux, masyarakat (khususnya yang tergolong menengah ke bawah) pada akhirnya mengabaikan lembaga pendidikan atau tidak sengaja kehilangan akses pendidikan akibat kehadiran sesuatu pada aspek struktural yang hanya menguntungkan secara individual atau kelompok tertentu.
Menurut Maleneo Bramasta alumni Politeknik Negeri Bali Jurusan DIII Akuntansi Neoliberalisme sebagai langkah awal fenomena privatisasi dan komersialisasi pendidikan tinggi telah melanggar inklusivitas yang seharusnya dijamin dalam Hak Atas Pendidikan. Universitas boleh saja beralasan bahwa ketimpangan yang terjadi disebabkan oleh terbatasnya kesempatan usaha, tetapi hal ini membuktikan bahwa otonomi pendanaan yang diberikan kepada PTN-BH pada dasarnya memang membebani mahasiswa. Ironinya, hasil pendidikan hanya mencetak kaum intelektual menjadi tenaga kerja murah.
“Dengan fakta ini, jika kita memasrahkan penyelenggaraan pendidikan untuk bergerak dalam kerangka neoliberalisme, maka pertemuan supply dan demand hanya akan berpusar di penduduk dengan pendapatan menengah ke atas. Mengapa? Karena universitas publik yang telah bergeser menjadi market brand dalam kerangka neoliberalisme membutuhkan uang besar untuk memenuhi standarisasi market brand lain di kompetisi global.” Tutupnya
Editor : Redaksi BJ/Sarjana
Sumber: mahasiswa FISIP UI serta anggota SEMAR UI