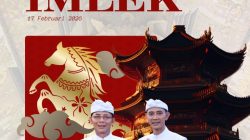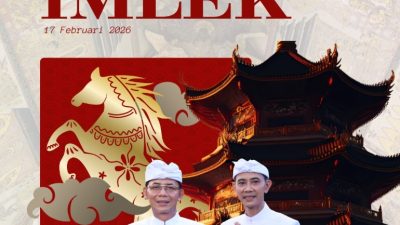Bali, Balijani.id| Mari bicara jujur. Di balik istilah megah Proyek Strategis Nasional, publik Bali sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sebidang demi sebidang benteng hidup pesisir berubah menjadi ruang ekspansi korporasi. Nama yang kini terus muncul di pusaran itu adalah BTID, perusahaan yang berdiri gagah dengan payung izin pusat, tetapi berdiri pula di atas wilayah yang secara fungsi ekologis tidak pernah dirancang untuk ditaklukkan.
Kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai bukan tanah kosong. Ia adalah sistem hidup, penahan abrasi, penyangga banjir, penyaring alami, dan rumah bagi ekosistem pesisir. Ketika kawasan seperti ini terseret ke dalam wilayah proyek bisnis, maka pertanyaannya bukan lagi ada izin atau tidak, tetapi apakah izin itu berdiri di atas hukum yang benar atau justru menabraknya.
Dan di sinilah masalahnya, izin pusat bukan berarti sebagai jubah suci dan kebal hukum. Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan, apalagi yang berfungsi lindung atau konservasi memiliki fungsi pokok sebagai penyangga kehidupan.
Perubahan peruntukan atau fungsi kawasan hutan tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus melalui prosedur ketat berbasis kepentingan ekologis jangka panjang. Jika proses itu cacat, maka dasar hukumnya bisa digugat.
Belum lagi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menegaskan bahwa kawasan konservasi seperti Tahura memiliki tujuan utama perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Artinya, logika utamanya adalah perlindungan, bukan eksploitasi.
Lalu ada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menegaskan prinsip kehati-hatian. Setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL yang sah, terbuka, dan akuntabel. Jika prosedur lingkungan dilanggar, izin lingkungan dapat dibatalkan, dan ketika izin lingkungan gugur, izin usaha ikut runtuh. Ini bukan opini, ini mekanisme hukum.
Ditambah lagi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa pemanfaatan ruang tidak boleh bertentangan dengan fungsi lindung suatu kawasan. Jika tata ruang dilanggar, izin yang terbit di atas pelanggaran itu dapat digugat dan dibatalkan melalui peradilan tata usaha negara.
Lebih spesifik lagi untuk wilayah pesisir, UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberi landasan tegas. Pasal 73 ayat 1 mangrove sebagai pohon abadi di wilayah konservasi dan lindung yang tidak boleh disertifikatkan, dipotong, dipadatkan, direklamasi dan dipindahkan dengan alasan apapun.
Dalam Pasal 73 juga mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang memanfaatkan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil tidak sesuai dengan peruntukan atau merusak ekosistemnya. Artinya, ketika mangrove bagian penting dari ekosistem pesisir dirusak atau dialihfungsikan tanpa kesesuaian peruntukan ekologisnya, itu bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi bisa masuk ranah pidana lingkungan.
Di tingkat daerah, regulasi daerah yang mempertegas perlindungan mangrove di Bali yaitu Pergub Bali No. 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pergub ini menegaskan bahwa mangrove memiliki fungsi lindung strategis dan setiap pemanfaatannya wajib menjaga kelestarian ekologis. Regulasi daerah ini memperkuat bahwa mangrove Bali bukan cadangan lahan investasi, melainkan zona perlindungan ekologis yang harus dijaga keberlanjutannya
Jadi narasi bahwa proyek besar otomatis kebal karena berlabel nasional adalah narasi yang menyesatkan. Hukum Indonesia tidak mengenal izin sakti.
Setiap izin tetap tunduk pada peraturan yang lebih tinggi, terutama yang menyangkut keselamatan lingkungan hidup.
Yang membuat situasi ini makin getir adalah konteks Bali sendiri. Pulau ini hidup dari keseimbangan. Falsafah Tri Hita Karana mengajarkan harmoni manusia dengan alam. Tapi apa yang terjadi ketika mangrove benteng alami justru diperlakukan sebagai cadangan lahan investasi. Itu bukan harmoni. Itu dominasi.
BTID mungkin merasa berdiri di jalur legal administratif. Tapi publik melihat sesuatu yang lain. Ekspansi yang terlalu percaya diri, terlalu cepat, dan terlalu sunyi dari transparansi. Dan semakin besar proyek berdiri di ruang hidup yang rapuh, semakin besar pula tanggung jawab hukumnya. Karena pada akhirnya, ini bukan soal anti pembangunan. Ini soal keliwat batas.
Dan ketika batas ekologis dilanggar, hukum memberi jalan untuk mengoreksi. Izin bisa diterbitkan oleh kekuasaan. Tapi pembatalan bisa datang dari hukum dan dari nurani publik yang menolak melihat benteng hidup Bali diperdagangkan.
[ Sarjana ]