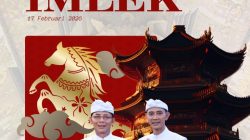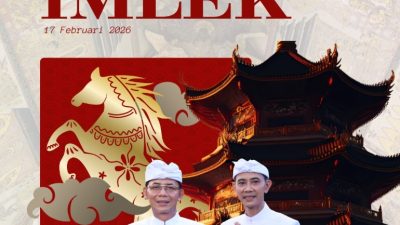Oleh : Laurensius Bagus Mahasiswa universitas Cokroaminoto Yogyakarta dan Aktivis Sosial
Yogjakarta, Balijani.id| Inflasi Indonesia memang disebut terkendali. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada akhir 2024 berada di kisaran 1,57 persen, angka yang bagi pemerintah menjadi bukti keberhasilan menjaga stabilitas harga. Namun bagi masyarakat, angka itu terasa tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Harga beras, cabai, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lain tetap merangkak naik. Narasi “inflasi rendah” terdengar indah di laporan resmi, tapi di meja makan rakyat, yang terasa justru semakin sempitnya ruang hidup.
Kenyataan ini mengungkap satu hal: angka makroekonomi tidak selalu menggambarkan realitas mikro. Meskipun inflasi nasional dikatakan stabil, biaya hidup meningkat lebih cepat daripada kenaikan upah. Di banyak kota besar, kelas pekerja mengeluhkan harga kontrakan dan transportasi yang naik, sementara gaji tak berubah berarti. Artinya, daya beli stagnan, bahkan menurun perlahan.
Di sisi lain, pemerintah terus menegaskan komitmennya menjaga daya beli rakyat lewat program subsidi energi. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan, belanja subsidi energi tahun 2024 mencapai sekitar Rp 169 triliun. Angka ini memang besar, tapi pertanyaan pentingnya adalah: apakah subsidi sebesar itu benar-benar dirasakan mereka yang paling membutuhkan?
Sebuah analisis dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) justru menyebut bahwa sekitar 40 persen manfaat subsidi energi di Indonesia dinikmati oleh kelompok rumah tangga berpendapatan tertinggi, sedangkan kelompok termiskin hanya menerima sekitar 1 persen. Ini bukan sekadar salah sasaran, melainkan cermin dari kebijakan sosial yang belum berpihak penuh pada keadilan.
Kondisi itu juga menunjukkan bagaimana subsidi seringkali lebih berpihak kepada konsumsi, bukan pada keberlanjutan ekonomi rakyat kecil. Nelayan kecil, misalnya, masih kesulitan mendapatkan solar bersubsidi di banyak daerah pesisir, sementara kendaraan pribadi dengan kapasitas besar bebas mengisi BBM bersubsidi tanpa kendala. Di sinilah terjadi ironi: negara menolong yang mampu, sementara yang lemah harus berebut sisa manfaat.
Pemerintah memang punya alasan kuat. Subsidi adalah cara cepat menahan gejolak harga dan menjaga inflasi tetap rendah. Namun cara cepat itu seringkali menutup jalan panjang menuju keadilan ekonomi yang sesungguhnya. Selama subsidi masih boros dan tidak selektif, keadilan hanya menjadi slogan, bukan kebijakan.
Menurut survei Indikator Politik Indonesia pada 2022, sebagian besar masyarakat (sekitar 58 persen responden) justru lebih setuju dengan subsidi harga barang daripada subsidi tunai. Mereka merasa subsidi harga lebih nyata dan mudah dirasakan langsung. Namun hasil survei ini juga mengungkap persoalan lain: masyarakat belum percaya bahwa subsidi tunai benar-benar tepat sasaran dan bebas dari kesalahan data. Artinya, masalah bukan hanya pada jenis subsidi, tetapi juga pada sistem pendataan dan distribusi yang belum transparan.
Dalam konteks yang lebih luas, keadilan ekonomi tidak bisa hanya diukur dari besarnya subsidi atau rendahnya inflasi. Keadilan harus tercermin dalam distribusi manfaat ekonomi. Jika subsidi besar justru memperkuat ketimpangan, maka sistem fiskal negara sedang berjalan di jalur yang salah. Dan ketika rakyat kecil masih kesulitan membeli beras di tengah inflasi rendah, maka angka-angka di atas kertas kehilangan makna sosialnya.
Kelas menengah yang dulu menjadi tulang punggung ekonomi kini juga mulai terjepit. Biaya hidup naik, cicilan rumah dan pendidikan anak membengkak, sementara kenaikan pendapatan tidak sebanding. Banyak keluarga kelas menengah harus menekan gaya hidup, bahkan menggunakan kartu kredit atau utang online untuk bertahan. Survei Bank Indonesia menunjukkan, tingkat konsumsi rumah tangga memang stabil, tapi sebagian besar dibiayai dari hutang konsumtif, bukan peningkatan pendapatan riil. Ini tanda bahaya bagi daya tahan ekonomi jangka panjang.
Masalahnya, kebijakan pemerintah masih berorientasi pada angka-angka makro: inflasi, pertumbuhan ekonomi, defisit APBN. Padahal, stabilitas makro tidak menjamin keadilan mikro. Ketika kebijakan lebih berfokus pada menjaga “stabilitas pasar” daripada “stabilitas dapur rakyat”, maka yang diuntungkan bukan rakyat, melainkan kepentingan ekonomi besar. Rakyat kecil hanya menikmati sisa keseimbangan, bukan hasil kesejahteraan.
Di sinilah pentingnya reposisi kebijakan ekonomi nasional. Subsidi perlu direformasi menjadi alat pemerataan sosial, bukan sekadar pengendali harga. Pemerintah perlu memperbaiki sistem data penerima manfaat—menggunakan data kependudukan dan data ekonomi mikro dari BPS—agar subsidi benar-benar menyentuh kelompok berpendapatan rendah. Selain itu, sebagian anggaran subsidi bisa dialihkan menjadi investasi sosial jangka panjang, seperti peningkatan produktivitas petani, bantuan alat nelayan, dan penguatan UMKM energi terbarukan. Dengan begitu, bantuan negara tidak berhenti di harga, tapi berlanjut pada kesejahteraan.
Selain itu, sistem upah juga harus dikoreksi. Jika harga terus naik, sementara upah riil tidak bertambah, maka inflasi rendah sekalipun tetap menyesakkan. Pemerintah bersama dunia usaha perlu memikirkan kembali formula upah minimum yang realistis terhadap kebutuhan hidup layak (KHL). Tanpa penyesuaian ini, kelas pekerja hanya menjadi penonton dari pertumbuhan ekonomi yang katanya “inklusif”.
Ketimpangan fiskal dan ketidakadilan subsidi juga menimbulkan dampak sosial. Di lapangan, kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi mulai menurun. Banyak warga menganggap subsidi bukan lagi bentuk kehadiran negara, melainkan permainan politik menjelang pemilu. Transparansi anggaran dan evaluasi berkala harus dilakukan terbuka agar rakyat tahu ke mana uang mereka mengalir dan siapa yang menikmatinya.
Keadilan ekonomi bukan soal seberapa besar anggaran digelontorkan, tapi seberapa adil manfaatnya dirasakan. Pemerintah boleh bangga dengan inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran lima persen, tetapi rakyat hanya akan percaya ketika harga sembako di pasar benar-benar stabil dan pendapatan mereka cukup untuk hidup layak.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya tetap sama: di mana letak keadilan ekonomi kita?
Selama subsidi masih lebih menguntungkan yang kuat, selama harga kebutuhan pokok masih naik tanpa pengendalian yang adil, dan selama pendapatan rakyat tak kunjung bergerak, maka keadilan ekonomi masih sekadar wacana. Inflasi boleh rendah, tapi rasa hidup makin berat. Dan selama itu terjadi, rakyat akan terus bertanya — bukan tentang angka, tapi tentang keadilan yang nyata.
[ Editor : Sarjana ]